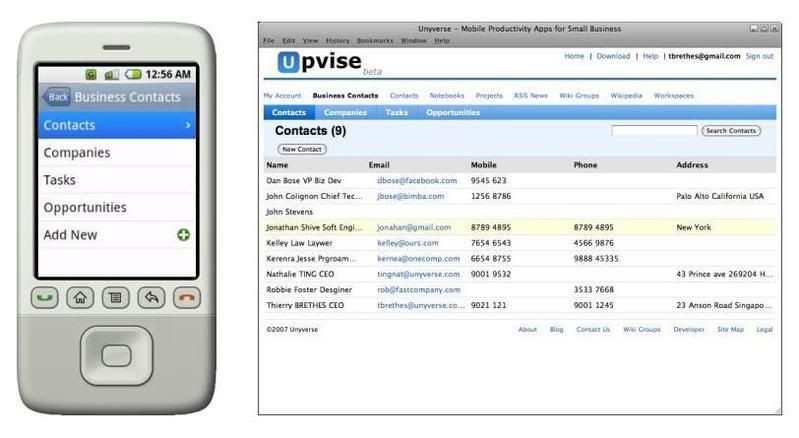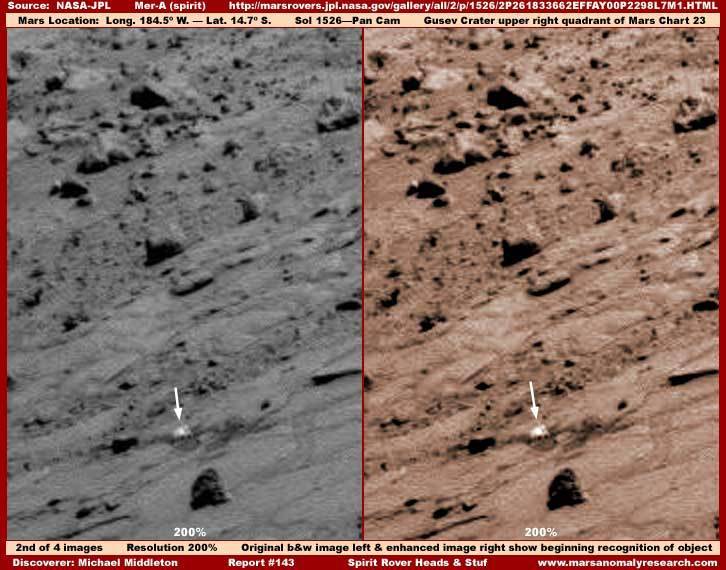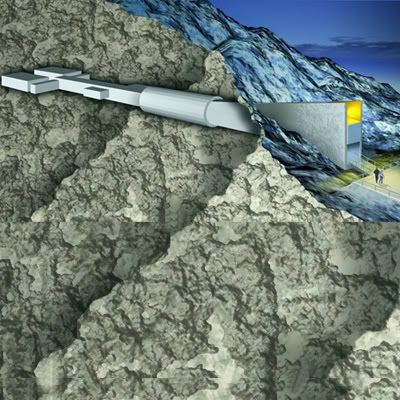Oleh Agus Wibowo
KITA telah memasuki Ramadhan 1429 H. Bagi masyarakat Jawa, bulan puasa atau pasa merupakan bulan penuh berkah sekaligus memiliki keistimewaan tersendiri. Itu karena dalam filosofi Jawa, puasa sering dinamakan prihatin, yaitu sebuah sarana mencapai derajat jalma winilis, atau manusia pilihan, yang dekat dengan Tuhan.
Maka, mereka mempersiapkan diri —baik lahir maupun batin— melalui serangkaian tradisi ritual berupa nyadran, padusan, dan megengan.
Tradisi nyadran, sebagaimana tradisi Jawa lain seperti muludan, suranan, dan syawalan, merupakan ritual memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan.
Esensi yang lain, yaitu sebagai simbolis hubungan diri orang Jawa dengan para leluhur, dengan sesama, maupun dengan Tuhan Sang Maha Pencipta.
Nyadran, kata Budi Puspo Priyadi (1989), memiliki kesamaan dengan tradisi craddha yang ada pada zaman Kerajaan Majapahit (1284). Kesamaannya terletak pada kegiatan manusia berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal.
Secara etimologis, kata craddha berasal dari bahasa Sansekerta sraddha yang artinya keyakinan, percaya, atau kepercayaan. Dahulu, masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal, sejatinya masih ada dan memengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunannya. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan saat atau waktu, hari dan tanggal meninggalnya leluhur.
Pada waktu-waktu itu, mereka yang masih hidup diharuskan membuat sesaji berupa kue, minuman, atau kesukakan orang yang me-ninggal.
Selanjutnya, sesaji itu ditaruh di meja, ditata rapi, diberi bunga setaman, dan diberi penerangan berupa lampu.
Prosesi nyadran saat ini dilakukan dengan ziarah sambil membersihkan makam leluhur, memanjatkan doa permohonan ampun, dan tabur bunga. Itu sebagai simbol bakti dan ungkapan terima kasih seseorang terhadap para leluhur-nya.
Kita akan merasakan nuansa magis dan unik dalam ritual nyadran. Keunikannya, selain menggunakan uba rampe tertentu, nyadran juga dilakukan di situs-situs yang dianggap keramat dan dipercaya semakin mendekatkan dengan Yang Kuasa.
Tempat-tempat itu, biasanya berupa makam leluhur atau tokoh besar yang banyak berjasa bagi syiar agama.
Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, masyarakat melaksanakan nyadran di makam Syekh Muchorodin atau Mbah Agung Mulyo. Adapun waktu pelaksanaan nyadran, biasanya dipilih pada tanggal 15, 20, dan 23 Ruwah atau Syaíban.
Mudhunan dan Munggahan
Pemilihan tanggal nyadran itu, kata Gatot Marsono (2007), di samping berdasarkan kesepakatan, juga berdasarkan paham mudhunan dan munggahan, yaitu paham yang meyakini bulan Ruwah sebagai saat turunnya arwah para leluhur untuk mengunjungi anak cucu di dunia.
Setelah melaksanakan tradisi nyadran, masyarakat Ja-wa biasanya melakukan penyucian diri melalui ritual yang disebut padusan. Prosesi padusan dimulai dengan mengguyur kepala dengan satu gayung air kembang. Seusai itu, sebuah wadah dari tanah liat yang juga berisi air dan kembang dibanting di depan kolam tempat padusan, sebagai penutup ritual.
Makna simbolis padusan, kata Tok Suwarto (2007), sebagai persiapan fisik dan batiniah agar hati menjadi bening, bersih, dan suci, sehingga ketika berpuasa tidak digoda oleh nafsu jahat dan hina.
Sebagaimana tradisi nyadran, padusan juga sangat unik karena pemilihan tempat yang tidak sembarangan. Misalnya, sumber-sumber air alam yang dianggap sakral, seperti Umbul Cokrotulung di Klaten, Umbul Pengging di Boyolali, Umbul Kayangan di Wonogiri, dan Umbul Berjo di Karanganyar.
Tradisi selanjutnya adalah upacara kenduri atau megengan, yang dilaksanakan menjelang tenggelamnya matahari di ufuk barat sehari sebelum 1 Ramadan. Kata megengan berasal dari bahasa Jawa megeng, yang berarti menahan.
Makna simbolisnya adalah, dalam memasuki puasa Ramadan orang Jawa terlebih dahulu harus berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan sosialnya. Pada prosesi megengan, biasanya dilantunkan doa-doa permohonan keselamatan dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Horizontal dan Vertikal
Serangkaian tradisi Jawa menjelang puasa itu, memiliki kearifan yang dalam. Pertama, sebagai sarana menciptakan relasi sosial kemasyarakat (horizontal) yang harmonis.
Nyadran, misalnya, tidak hanya sekadar gotong-royong membersihkan makam leluhur, selamatan dengan kenduri, dan membuat kue apem ketan kolak sebagai unsur utama sesaji. Lebih dari itu, menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jatidiri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme.
Hal itu terlihat dalam prosesi nyadran, yaitu saat kelompok-kelompok keluarga atau trah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Perbedaan itu lebur, karena mereka berkumpul menjadi satu, berbaur, saling mengasihi dan menyayangi satu dengan yang lain.
Bahkan, seusai nyadran ada warga yang mengajak saudara di desa ikut merantau dan bekerja di kota-kota besar. Dalam konteks itulah, ada hubungan kekerabatan, kebersamaan, kasih sayang, di antara warga atau anggota trah. Terasa sekali, warga sekampung seakan satu keturunan.
Spirit nyadran itu bila dibawa dalam konteks negara, maka akan menjadikan Indonesia yang rukun, ayom, ayem, dan tenteram.
Kedua, wujud penghargaan kepada leluhur atau pendahulu. Mereka yang pulang dari rantauan, mengaitkan nyadran dengan sedekah, beramal kepada para fakir miskin, membangun tempat ibadah, serta memugar cungkup dan pagar makam. Kegiatan tersebut sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur, yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak, hingga menjadi orang yang sukses.
Singkatnya, mereka ingin njaga prajane sing wis sumare atau usaha anak untuk menjaga citra, wibawa, dan nama baik leluhur-nya.
Ketiga, budaya membersihkan jasmani dan rohani ketika hendak beribadah atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebersihan jasmani melalui ritual padusan, diharapkan akan menyucikan hati dari segenap perasaan iri, dengki, hasut, takabur, dan menipu.
Kesucian padusan itu, jika dibawa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menjauhkan elite politik dan anggota legislatif dari perbuatan menjilat, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pada akhirnya, serangkaian tradisi Jawa menjelang pelaksanaan puasa, patut terus dipertahankan. Bukan hanya berbagai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, lebih dari itu sebagai wujud pelestarian budaya adhiluhung peninggalan nenek moyang. Semoga!(68)
— Agus Wibowo, pemerhati budaya dan penulis buku ”Memayu Hayuning Bawono”.